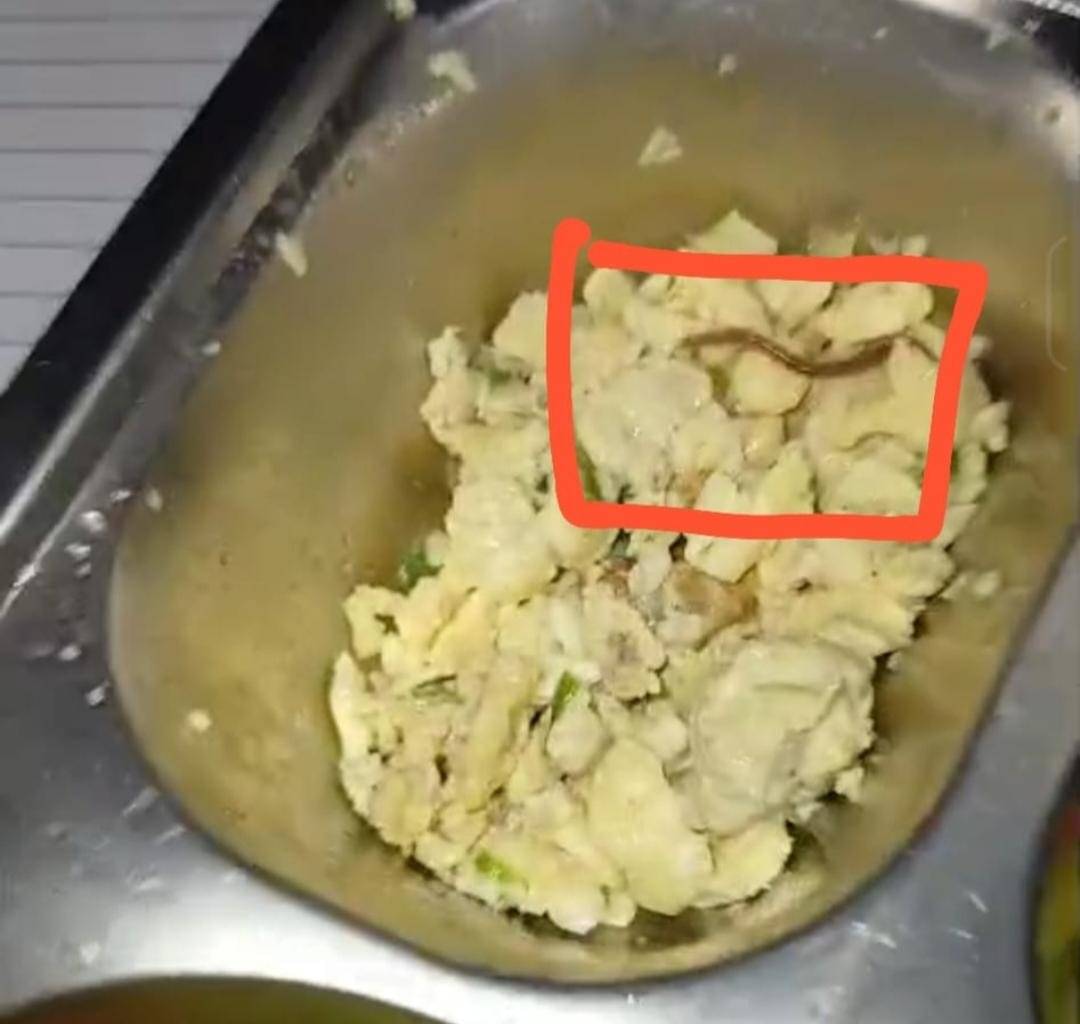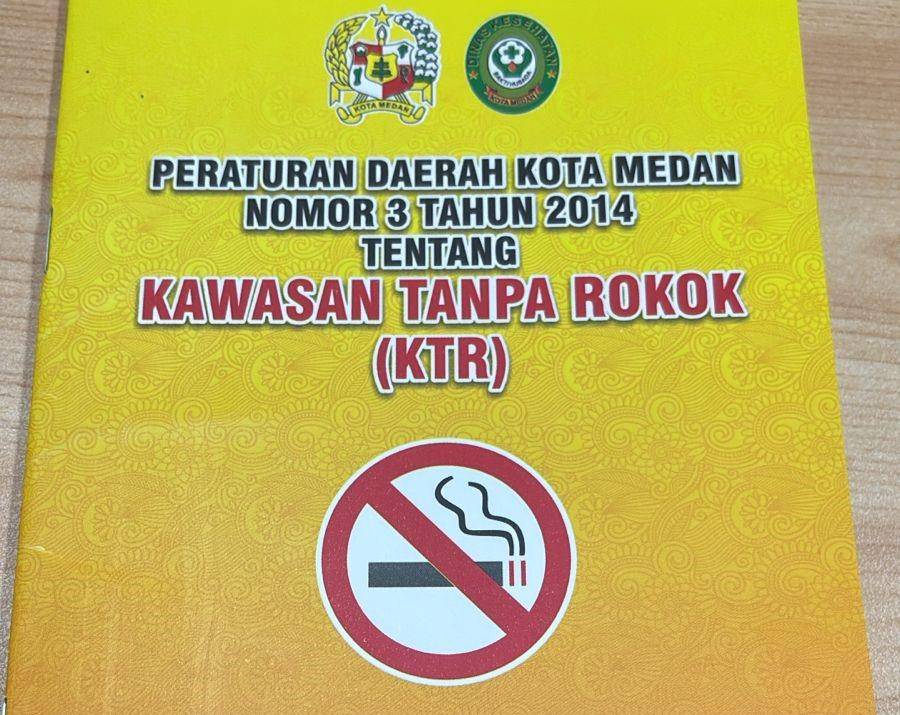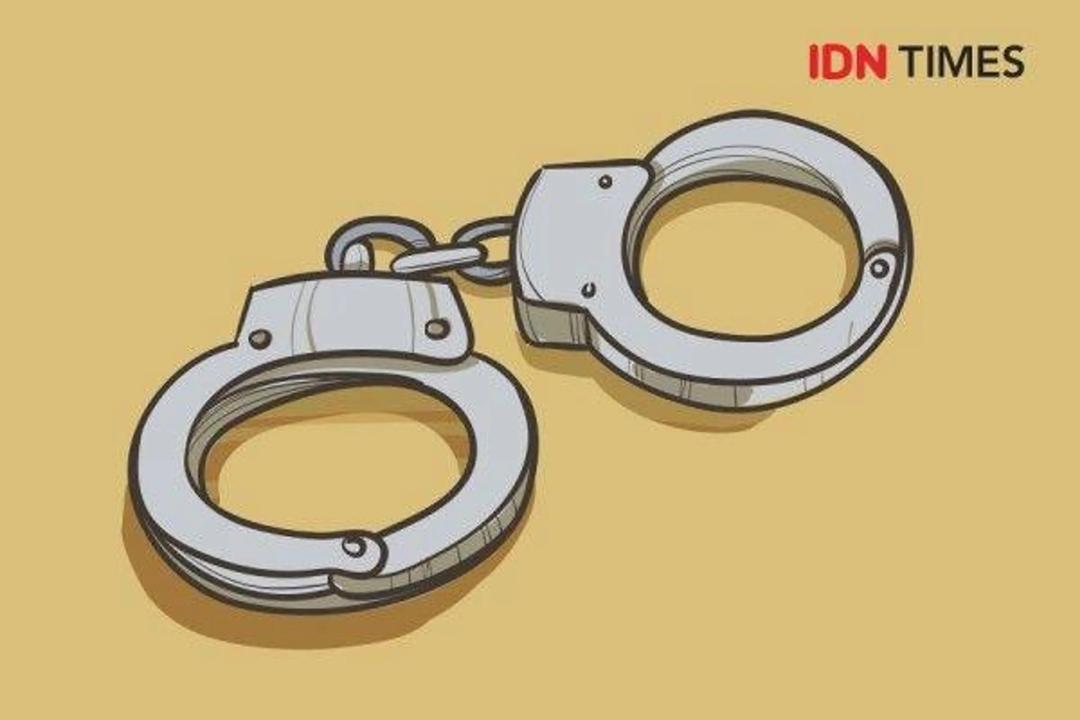COP30, Menakar Keberpihakan Pemerintah Terhadap Hutan Adat

Medan, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) menilai pemerintah belum benar-benar serius dalam memenuhi janji percepatan pengakuan hutan adat. Padahal, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat menyampaikan komitmen itu di ajang Konferensi Iklim PBB (COP30) di Brasil, 4 November 2025 lalu.
Namun, realitanya kebijakan negara masih belum berpihak pada Masyarakat Adat yang selama ini menjaga hutan dan tanah mereka secara turun-temurun.
“Negara tidak serius dalam memenuhi, memajukan, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Adat,” kata Yokbeth Felle, Staf Kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dalam diskusi #TheAnswerisUs: Suara Masyarakat Adat Bagi Keadilan Iklim, Rabu (12/11/2025) dilansir dari kanal COP30 laman Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Jumat (14/11/2025).
1. Relasi masyarakat adat dengan hutan lebih dari sekadar sumber daya

Selama ini, negara melihat hutan dan tanah hanya sebagai objek ekonomi. Namun bagi Masyarakat Adat, keduanya adalah bagian dari kehidupan.
“Masyarakat Adat memandang hutan dan tanah sebagai ibu, bahkan ada yang menganggapnya bagian dari tubuh. Ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu pemuda suku Moi di wilayah Sorong. Ia menegaskan bahwa kalau sampai tanah hilang, berarti marga yang meninggali tanah itu juga hilang,” kata Yokbeth.
Ia juga mencontohkan kisah Mama Alowisia, perempuan adat Suku Yei di Merauke, Papua Selatan, yang menolak pembukaan hutan karena keberlangsungan hidupnya bergantung pada pohon nibung—pohon penting bagi perempuan adat untuk menampung air pati sagu.
“Nibung ini dapat di hutan, makanya mama tidak suka dong bongkar hutan,” ujar Yokbeth menirukan ucapan Mama Alowisia.
2. Lambatnya pengakuan hutan adat, cepatnya izin proyek ekstraktif

Meski sudah 13 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, pengakuannya di Papua berjalan sangat lambat.
Menurut catatan Yayasan Pusaka, sejak 2016 hingga Oktober 2025, penetapan hutan adat di seluruh Papua baru mencapai 39.912 hektare. “Ini ironis, setelah 13 tahun putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan hutan adat di Papua baru hanya seluas 39,9 ribu hektare dari potensi luasan 12,466 juta hektar,” kata Yokbeth.
Ironinya, pemerintah justru cepat memberikan izin bagi proyek-proyek ekstraktif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025, sekitar 587.750 hektare kawasan hutan di Papua Selatan diubah peruntukannya untuk proyek ekstraktif.
“Proses untuk memberikan izin pada proyek ekstraktif itu lebih cepat dibandingkan memberikan pengakuan hutan adat,” tegasnya.
3. Masyarakat adat dianggap solusi krisis iklim, bukan penghambat

Deputi II Bidang Advokasi dan Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi, menegaskan bahwa Masyarakat Adat justru bagian dari solusi krisis iklim, bukan penghambat pembangunan.
“Sejak lama Masyarakat Adat telah menjaga hutan dengan kearifan lokal mereka. Yang dibutuhkan adalah jangan mengganggu praktik baik yang dilakukan oleh Masyarakat Adat. Jangan menganggap bahwa Masyarakat Adat itu terbelakang,” katanya.
Menurut Mega Ayu Lestari dari Working Group ICCAs Indonesia (WGII), praktik konservasi yang dilakukan Masyarakat Adat telah mencakup 647.457 hektare lahan. “Praktik konservasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal ini merupakan solusi dari level akar rumput, yang seharusnya diakui dan dipromosikan oleh negara,” ujarnya.
Namun, Erasmus menilai pengakuan itu masih setengah hati karena belum adanya payung hukum khusus. “Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi mendesak dan harus diprioritaskan,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, mengakui masih ada hambatan di lapangan. “Salah satu masalah yang memperlambat proses pengakuan hutan adat adalah keterbatasan sumber daya yang ada di masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat dengan target 1,4 juta hektare hingga 2029. “Desember 2025 nanti rencana kami melakukan konsultasi publik untuk draft roadmap percepatan penetapan status hutan adat,” ujar Julmansyah.