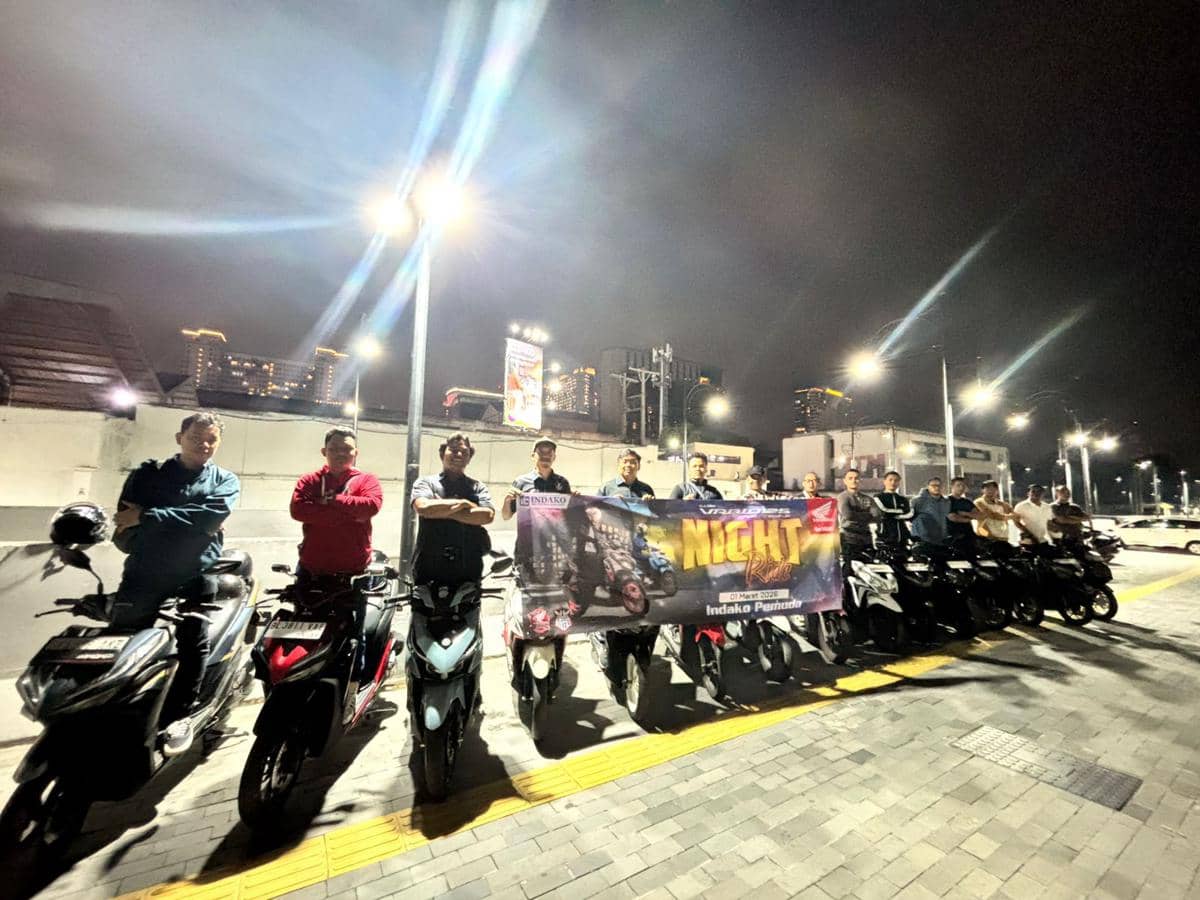Ironi Dunia Kesehatan, Kolegium Dinilai 'Dibonsai' oleh Omnibus Law

Medan, IDN Times - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumut, Rizky Adriansyah menyampaikan pendapatnya bahwa negara sedang tergesa-gesa karena Indonesia kekurangan dokter. Terutama spesialis.
"Kalimat itu diucapkan dengan wajah prihatin, lalu disusul daftar target: berapa ribu yang harus “diproduksi”, berapa tahun yang harus “dipangkas”, berapa aturan yang harus “disederhanakan”. Seolah-olah pendidikan dokter spesialis adalah lini perakitan: masuk bahan baku, keluar barang jadi, lalu statistik pun tersenyum," jelasnya.
Baginya, di titik inilah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (omnibus law) menjadi panggung utama, yang datang membawa janji transformasi kesehatan. Namun, seperti banyak omnibus lain, yang disebut “transform” sering berarti satu hal: memusatkan kendali.
"Yang paling terasa bukan cuma pada tata kelola layanan, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih sensitif: kolegium—penjaga standar kompetensi, kurikulum, dan mutu pendidikan kedokteran," kata dokter anak ini.
1. Kolegium seharusnya bekerja seperti rem sekaligus kompas

Masih dalam penjelasannya, kolegium seharusnya bekerja seperti rem sekaligus kompas. Rem agar profesi tidak tergelincir mengejar kecepatan. Kompas agar arah pendidikan ditentukan oleh ilmu, bukan oleh suasana rapat.
Dalam sistem yang sehat, kolegium berdiri pada jarak aman dari kekuasaan. Bukan karena anti pemerintah, melainkan karena ia sedang menjaga sesuatu yang negara juga butuhkan: mutu dokter dan keselamatan pasien.
"Tapi 'omnibus' punya selera lain. Ia menyukai struktur yang rapi, garis komando yang jelas, dan koordinasi yang tidak berisik. Di atas kertas, itu terdengar modern. Di lapangan, modern sering berubah menjadi “jangan banyak tanya”. Kolegium pun mulai tampak seperti benda yang hendak dipindahkan dari ranah otonomi ilmiah ke ranah administrasi. Dari peer review ke policy compliance. Dari rapat ilmiah ke rapat target," sambungnya.
2. Dokter Rizky beri saran terkait masalah pendidikan dokter spesialis

Menurutnya, masalah pendidikan dokter spesialis memang ada. Seperti akses mahal, sebaran tidak adil, kapasitas rumah sakit pendidikan terbatas, kultur feodal masih hidup di beberapa tempat. Namun, obatnya tidak harus merobohkan pagar. Jika persoalannya distribusi, benahi insentif dan fasilitas. Jika persoalannya pembiayaan, tanggung dengan skema yang masuk akal. Jika persoalannya tata kelola pendidikan, tertibkan secara transparan. Namun yang terjadi, justru mekanisme penjaga mutu ikut “dirapikan”.
"Di sinilah ironi dimulai. Negara bilang ingin meningkatkan kualitas layanan. Tapi langkah yang membuat orang gelisah justru langkah yang membuat standar mudah ditawar. Bukan dengan pengumuman 'standar diturunkan'—itu terlalu jujur. Caranya lebih elegan: ubah struktur, ubah kewenangan, ubah cara pengambilan keputusan. Standar tetap 'tinggi' di panggung, tetapi kelenturannya meningkat di belakang layar," ungkapnya.
Kolegium yang kehilangan jarak dari kekuasaan menghadapi konflik kepentingan permanen: di satu sisi harus menjaga standar, di sisi lain ditarik untuk mempercepat produksi.
"Dan kita tahu siapa yang biasanya menang dalam tarik-menarik semacam itu. Ilmu tidak punya anggaran. Ilmu tidak punya target triwulan. Ilmu tidak bisa menjanjikan tepuk tangan di konferensi pers. Yang bisa memberi “capaian” adalah angka," tuturnya.
"Lahirlah pertanyaan yang tidak nyaman: ketika kebijakan menuntut percepatan, apakah kolegium masih bebas berkata “tidak”? Bebas berkata, “belum siap”, “belum memenuhi”, “ini berbahaya”? Atau ia akan belajar bahasa baru: “disesuaikan”, “dioptimalisasi”, “dipermudah”? Dalam birokrasi, kata “optimalisasi” sering berarti “tolong jangan menghambat," tambah Ketua IDAI Sumut ini.
3. Dinilai bukan soal martabat profesi tapi soal publik

Dia menilai, masalahnya bukan semata soal martabat profesi. Namun, soal publik.
Pasien tidak peduli struktur kelembagaan. Pasien hanya ingin satu hal: dokter yang kompeten, sistem yang aman. Tetapi kompetensi tidak tumbuh dari slogan. Ia tumbuh dari proses pendidikan yang ketat, evaluasi yang jujur, dan standar yang konsisten. Jika standar bisa berubah karena pergantian program, maka yang berubah bukan hanya dokumen. Yang berubah adalah kualitas tindakan klinis di ruang perawatan.
"Pendidikan dokter spesialis bukan proyek musiman. Ia investasi puluhan tahun. Menanamnya dengan logika target tahunan sama saja memaksa pohon berbuah sebelum akarnya kuat. Hasilnya mungkin tampak ramai di laporan, tetapi rapuh di kenyataan. Dan kerapuhan dalam kedokteran bukan sekadar salah angka. Ia bisa menjadi salah diagnosis, salah pengobatan, salah tindakan, salah keputusan yang tak bisa diputar ulang," ucap Rizky.
Pendukung omnibus law akan berkata “Tenang, negara juga peduli mutu.” Tentu. Hampir semua orang peduli mutu—di atas kertas. Ujian sesungguhnya adalah desain yang membuat mutu kebal terhadap kepentingan jangka pendek. Kolegium yang independen adalah mekanisme kebal itu. Bukan 'klub eksklusif' yang harus dipertahankan demi gengsi. Bahkan, justru pagar agar pasien tidak menjadi korban dari kebijakan yang terlalu percaya diri pada angka.
Sehingga, kegelisahan terhadap omnibus law bukan paranoia. Ini refleks wajar ketika lembaga penjaga standar didekatkan ke pusat komando. Kalau negara ingin memperbanyak dokter spesialis, lakukan dengan cara yang tidak mengorbankan rem keselamatan pasien. Bangun kapasitas RS pendidikan, perbaiki distribusi, bereskan pembiayaan dan kultur. Jangan jadikan kolegium semacam “unit produksi” yang harus patuh pada kecepatan mesin.
"Boleh saja negara memimpin. Tapi dalam urusan standar kompetensi, negara seharusnya memimpin dengan satu cara: memastikan ada lembaga ilmiah yang berani melawan negara ketika negara keliru. Itulah gunanya independensi. Jika kolegium akhirnya hanya menjadi stempel kebijakan, kita akan punya banyak dokter di statistik—dan banyak kegelisahan di ruang praktik. Negara mungkin mendapat angka. Publik yang menanggung risikonya," tandasnya.